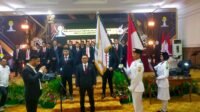Oleh : Elfahmi Lubis**
Bengkulu – Polemik soal Pilpres 2024, sudah game over, baik secara yuridis maupun politis. Besok, Rabu (24/04/2024) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar sidang pleno penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2024. Selanjutnya SK Penetapan KPU RI tersebut menjadi dasar pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) Periode 2024-2029 oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Dalam tulisan sederhana ini saya ingin mengulik beberapa terobosan hukum yang terjadi sepanjang persidangan sengketa PHPU Pilpres 2024 di MK. Catatan dari orang yang tidak pernah absen mengikuti segala dinamika persidangan PHPU dari awal sampai kemaren pembacaan putusan. Banyak pelajaran, ilmu, dan wawasan yang diperoleh. Bahkan, sampai hal-hal kecil seperti teknik bertanya para hakim mahkamah, kuasa hukum pemohon, termohon, pihak terkait, dan ahli tidak luput dari perhatian saya. Tidak itu saja sampai soal fashion para pihak yang terlibat selama proses persidangan, menjadi atensi. Hal serupa pernah saya lakukan pada persidangan pidana kasus Kopi Sianida dan Sambo. Semuanya tidak akan pernah kita peroleh dari buku dan dogma-dogma tertulis dalam literatur hukum yang selama ini kita pelajari.
Catatan sederhana ini, saya sebut dengan istilah “EKSAMINASI MINOR” putusan MK dalam sengketa PHPU Pilpres 2024.
Setidaknya ada beberapa hal baru (terobosan) hukum yang terjadi dalam sengketa PHPU, yaitu pertama, adanya dissenting opinion dari 3 orang hakim pemeriksa perkara, dimana dalam sengketa PHPU Pilpres baru kali ini ada hakim dissenting. Merujuk pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD, selama ini tradisi dissenting opinion sengaja tidak diberikan ruang kepada para hakim pemeriksa perkara PHPU Pilpres. Alasannya, putusan MK soal sengketa PHPU Pilpres harus bersifat bulat, artinya tidak ada perbedaan pendapat dari para hakim karena menyangkut soal legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan, jika masih ada perbedaan tajam antar hakim terkait putusan, dilakukan berkali-kali rapat permusyawaratan hakim sampai akhirnya semua hakim mahkamah memiliki pendapat yang sama soal putusan yang akan dijatuhkan oleh mahkamah. Namun tradisi ini sepertinya dalam sengketa PHPU Pilpres 2024 tidak berlaku lagi, terbukti ada 3 orang hakim menyatakan dissenting opinion dari 8 hakim mahkamah yang terlibat dalam pemeriksaan perkara.
Saya sendiri mengapresiasi sikap yang diambil 3 orang hakim yang mengajukan dissenting opinion. Setidaknya, sikap 3 orang hakim ini bisa mewakili perasaan dan ekspektasi sebagian orang yang menginginkan mahkamah tidak terjebak pada persoalan formil atau prosedural saja, tapi berpikir kepada hal-hal yang subtantif atau kualitatif. Keinginan agar hakim mahkamah menerapkan hukum progresif, setidaknya tercermin dari sikap 3 orang hakim yang melakukan dissenting opinion. Namun tesis saya ini bukan bertujuan ingin menegasi apalagi mendegradasi bahwa 5 orang hakim yang tidak mengajukan dissenting opinion tersebut tidak progresif dan subtantif. Saya melihatnya lebih pada persoalan perbedaan perspektif dan keyakinan masing-masing hakim dalam melihat fakta-fakta dan suasana kebatinan di publik. Toh, kehadiran dissenting opinion tidak berarti putusan MK “cacat” atau tidak legitimate, karena sudah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari pertimbangan dan amar putusan. Dalam konteks ini, 8 orang hakim MK telah membuat suatu putusan bulat, tanpa lagi mempersoalkan apakah ada hakim yang dissenting opinion atau tidak. Dengan demikian, kita tidak membangun narasi “sesat” kepada publik, seolah-seolah dissenting opinion merupakan bagian tersendiri atau terpisah diluar putusan MK.
Perkara PHPU Pilpres ini menuntut hakim benar-benar berjiwa negarawanan, karena salah dalam menjatuhkan putusan akan menimbulkan implikasi serius pada aspek-aspek non hakim, sepertinya krisis politik dan sosial yang bisa mengancam disintegrasi bangsa.
Harus dipahami bahwa esensi tradisi dissenting opinion hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak lebih dari upaya peradilan mewujudkan akuntabilitas putusannya, dengan memberikan hak kepada setiap hakim pemeriksa perkara untuk menentukan sikap dan konsistensinya terhadap suatu perkara yang akan diputuskan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap publik yang ingin berpartipasi dalam memberikan pendapat hukum atau dukungan moral kepada pengadilan dengan cara mengajukan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dan eksiminasi putusan yang dilakukan para pakar dan ahli.
Merujuk Black Law Dictionary, pengertian dissenting opinion adalah: An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. — Often shortened to dissent. — Also termed minority opinion. Yakni, pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas.
Dissenting opinion sendiri, pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu mengatur bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
Khusus dalam sengketa konstitusi di MK, sebenarnya dissenting opinion diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.
Kedua, diakomodirnya Amicus Curaie yang berbagai pihak dalam pertimbangan putusan MK, dan ini belum pernah terjadi dalam putusan sebelumnya, baik dalam sengketa PHPU Pilres, Pileg, Pilkada (baca Pemilu) maupun dalam permohonan uji materi UU terhadap UUD NRI 1945. Hal ini membuktikan bahwa hakim MK sangat terbuka dalam menyerap aspirasi dan rasa keadilan di masyarakat. Dengan demikian membantu hakim dalam “meresepi” keyakinan utuh dalam memutuskan suatu perkara krusial dan berdampak luas pada aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Saya, menilai amicus curaie suatu tradisi hukum yang perlu terus didorong karena sekaligus bentuk partisipasi publik mengawasi peradilan dan para hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dijamin akuntabilitasnya. Saya mengusulkan agar amicus curaie dapat dapat diformalkan pengaturannya dalam hukum positif sehingga keberadaanya secara yuridis dan moral menjadi kuat. Walaupun apa yang telah dilakukan sebenarnya bisa menjadi yurisprudensi.
Ketiga, adanya perluasan dalam hukum acara MK, dimana majelis hakim konstitusi mengagendakan acara penyampian kesimpulan dari pemohon, termohon, dan pihak terkait, yang sebenarnya tidak diatur dalam hukum acara MK. Saya melihat munculnya acara penyampaian kesimpulan ini sebagai upaya mahkamah untuk pendalaman subtansi perkara. Soalnya, dengan waktu 14 hari yang diberikan UU kepada MK untuk menyelesaikan sengketa PHPU Pilpres, sangat tidak memadai untuk dapat menggali fakta secara mendalam dan subtantif. Melalui penyampaian kesimpulan para pihak ini, hakim dapat memperoleh perspektif lain dalam menjatuhkan putusan, selain fakta dan alat buktinyang terungkap dalam persidangan.
Keempat, adanya pemanggilan pada pihak pemberi keterangan (menteri/setingkatnya) tapi itu hanya hakim yang boleh bertanya, sementara ruang yang sama tidak diberikan kepada pemohon, termohon, dan pihak rerkait. Hal ini juga menurut saya bentuk atau cara hakim mahkamah melakukan pendalaman fakta dan subtansi untuk kepentingan para hakim sendiri dalam membuat putusan.
Selain keempat hal diatas, belajar dari sengketa PHPU Pilpres 2024, banyak hal yang perlu dilakukan dalam aspek pengaturan regulasi Pemilu, oleh sebab itu revisi UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi agenda mendesak. Persoalan pengaturan penyelesaian sengketa Pemilu, seperti sengketa administrasi, proses, dan tindak pidana Pemilu. (khusus soal pidana pemilu dan urgensi keberadaan Sentra Gakkumdu, saya sedang menulis buku tentang ini dan dalam penyelesaian akhir, insyaallah akan segera terbit).
Lemah dan sangat terbatasnya kewenangan yang diberikan UU kepada Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu, ikut berkontribusi sulitnya mengurai sengkarut persoalan yang muncul pada setiap Pemilu. Akibatnya banyak praktek-praktek pelanggaran maupun kejahatan Pemilu, yang mengusik rasa keadilan masyarakat maupun peserta tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu. Begitu juga pengaturan soal netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pemilu, serta pengaturan penyaluran Bansos oleh patahana harus menjadi agenda bersama untuk dituntaskan aspek regulasinya. Oleh sebab itu gagasan tentang MAHKAMAH PEMILU menjadi relevan kembali untuk dibahas dan diwujudkan. Termasuk juga gagasan apakah perlu Pilkada dikembalikan kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Semoga mencerahkan. Tabik.
** Penulis merupakan Akademisi/Ketua LBH AP Muhammadiyah)